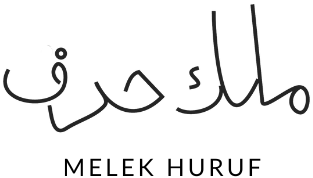Oleh Gin Teguh
Ada kekerasan yang tidak datang dengan ancaman. Sebagian justru hadir melalui bahasa yang rapi, kutipan sastra, pujian, dan kedekatan intelektual. Fang Si-Chi’s First Love Paradise bergerak persis di wilayah itu: wilayah di mana kata-kata menjadi pintu masuk bagi kehancuran, dan sastra yang seharusnya membebaskan dipelintir menjadi jerat kekuasaan.
Terlepas dari sejumlah masalah pada terjemahan bahasa Indonesia, seperti pilihan diksi yang tidak selalu presisi, baris narasi yang terputus, kehilangan kontinuitas di beberapa bagian, novel karangan Lin Yi-Han ini tetap menembus lapisan emosi terdalam. Ada sesuatu yang tak bisa diredam oleh ketidaksempurnaan teknis, yakni luka yang dituliskan dengan kejujuran yang nyaris telanjang.
Novel ini terbagi dalam tiga bagian, dan dibuka dengan kisah persahabatan dua gadis remaja: Fang Si-Chi dan Liu Yi-Ting. Keduanya cerdas, mencintai sastra dan seni, dan “lebih dewasa” dibanding teman-temannya. Hal itu menjadikan mereka lebih dekat dengan orang dewasa, terlebih yang punya banyak pengetahuan, contohnya Guru Lee Guo-Hua.
Kekaguman mereka pada Guru Lee, seorang pengajar sastra, awalnya terasa wajar. Ia berpengetahuan luas, fasih mengutip karya klasik Eropa dan Tiongkok, dan tahu bagaimana berbicara kepada remaja yang ingin diakui kecerdasannya. Namun kekaguman itu perlahan membuka celah bagi malapetaka. Guru Lee memanfaatkan kecerdasan dan posisi kuasanya untuk membingkai kekerasan sebagai cinta kepada Si-Chi.
Salah satu kekuatan dari novel ini adalah caranya menggambarkan keterikatan traumatis. Si-Chi bukan tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang keliru. Namun, usia yang terlalu belia dan kekaguman yang telanjur dalam, membuat perlawanan menjadi nyaris mustahil. Kekerasan pun dikenali sebagai makna. Si-Chi merasionalisasi luka. Ia terombang-ambing dalam pikirannya sendiri, berusaha memahami bias perasaannya: antara takut, kagum, dan rasa memiliki. Pada beberapa momen, kekerasan bahkan tampak “wajar,” sebuah paradoks yang justru memperlihatkan betapa dalamnya manipulasi Guru Lee. Di sinilah psikoanalisis menjadi kunci pembacaan. Yang dialami Si-Chi bukan sekadar pemaksaan fisik dan seksual, melainkan pembentukan ikatan psikis, di mana rasa takut, bersalah, dan kebutuhan akan pengakuan bercampur menjadi satu.
Kesadaran Si-Chi datang perlahan, tapi lingkungan tidak memberi ruang aman. Orang tua tak menaruh curiga. Dan, Yi-Ting, sahabatnya, justru menjauh oleh rasa iri. Ketika Yi-Ting akhirnya menemukan buku harian Si-Chi, yang merupakan titik awal bagian kedua novel, semuanya sudah telanjur runtuh. Bagian ini ditulis dengan intensitas yang menyesakkan: gelap, berat, nyaris tanpa jeda. Manipulasi Guru Lee yang menguasai perasaan Si-Chi selama bertahun-tahun, menjadi selubung bagi hasrat yang menyimpang.
Ketika kesadaran akhirnya menembus ilusi, yang muncul bukan pembebasan, melainkan rasa bersalah. Si-Chi menyalahkan diri, merasa kotor dan hina. Ini bukan respons yang ganjil, melainkan pola traumatis yang dikenal luas: korban menginternalisasi kekerasan sebagai aib personal. Terlebih, ironi kecantikan dan kemolekan tubuhnya justru dianggap sebagai penyebab. Sebuah logika kejam yang membuatnya menjauh.
Bagian akhir novel memperlihatkan kehancuran psikis Si-Chi: kehilangan kewarasan dan ingatan. “Sebenarnya, aku sudah mati saat memikirkan kematian. Hidup itu seperti pakaian, sangat mudah untuk ditanggalkan dan direnggut,” tulisnya. Ini bukan metafora berlebihan, melainkan pernyataan tentang hidup yang telah putus.
Paradoks paling getir hadir di ujung: dunia di sekitar tetap berjalan, bahkan pelaku hidup baik-baik saja. Justru inilah yang membuat novel ini terasa begitu nyata dan begitu menyakitkan. Apalagi setelah mengetahui bahwa kisah ini berakar pada pengalaman Lin Yi-Han, sang penulis yang hidupnya berakhir tragis tak lama setelah bukunya terbit.
Fang Si-Chi’s First Love Paradise bukan karya sastra yang menawarkan hiburan. Ia menuntut pembaca untuk tinggal bersama ketidaknyamanan, menatap keterikatan yang menyakitkan tanpa jalan pintas moral. Entah berapa kali saya terhenti membacanya demi menarik napas. Dalam kejujurannya yang gelap dan getir, novel ini dengan tegas menyatakan bahwa luka para penyintas itu nyata, dan kesunyian tidak harus membunuh mereka.

Gin Teguh adalah seorang penulis yang melahirkan novel, fiksi pendek, dan buku-buku anak. Belakangan, dia mulai menulis skenario dan menyutradarai film. Dua film pendek arahannya, Ibu Ora Sare (2021) dan Dengung lebah (2023), pernah diputar di beberapa festival film serta meraih apresiasi. Debut film panjangnya sebagai penulis skenario, Aum! (2021), membawanya mendapatkan nominasi Penulis Skenario Asli Terbaik di Piala Maya. Kini, selain sedang mempersiapkan film-film berikutnya, dia terus menulis buku-buku.