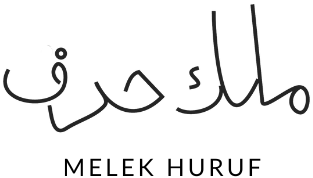Oleh Chairumi Tyas Satiti
Sampulnya terlihat seperti gambar cerita anak-anak (memang benar), meskipun judulnya terdengar garang dan menegangkan. Genre buku yang satu ini unik: sastra klasik masa kecil. Genderang Perang dari Wamena begitu singkat dan polos, meninggalkan cerita untuk didiskusikan dan kelanjutan untuk diimajinasikan.
Genderang Perang dari Wamena mengisahkan petualangan dua sahabat, Adi dan Yun, yang menemukan genderang di gudang rumah Adi. Genderang itu merupakan salah satu barang pusaka yang “dititipkan” kepada Ayah Adi, yang bekerja di museum sebuah universitas di Belanda. Ketika Yun menabuhnya di dalam gudang, ia tak bisa berhenti, dan setiap kali kabut tipis pelan-pelan mulai menyelimuti ruangan, mereka pun terlempar ke hutan rimba di pedalaman Papua.
Adi dan Yun menabuhnya berkali-kali, untuk menyingkap misteri, dalam penggalan demi penggalan cerita setiap mereka dalam pengaruh genderang. Dari dibuat penasaran, saya jadi agak tidak punya banyak ekspektasi, lalu dibuat penasaran lagi, dan dibuat tegang. Saya senang dengan bagian ending-nya, yang, kalau kita baca duluan sebelum baca keseluruhan bukunya, justru bikin semakin ingin baca.
Bagian paling menarik buat saya justru cerita pertandingan kasti. Adegan gelut yang lucu di desa ini cukup realistis, cukup bikin gemas, dan ending-nya cukup menarik. Benar-benar membangkitkan rasa ingin bermain dan kenangan masa kanak-kanak saya (meskipun saya takut berantem).
Novel ini menyebut istilah yang sebelumnya pernah saya dengar, dan tidak saya ketahui. Selama ini, yang diajarkan kepada saya adalah rumah tradisional suku di Papua bernama honai, tetapi baru saya tahu bahwa ada honae (rumah khusus untuk laki-laki) dan iweuma (rumah untuk perempuan).
Kala membaca buku ini, saya sedang gandrung membaca buku-buku “klasik” semacam Wuthering Heights, Anna Karenina, atau Emma. Saya memahami kenapa serial ini menjadi “klasik,” selayaknya buku-buku Enid Blyton dan Sir Arthur Conan Doyle: tema dan ceritanya masih mengagumkan untuk dibaca sampai kapan pun.
Saya membayangkan jika anak saya kelak, atau saya saat berusia 10 tahun membacanya, mungkin kami akan jadi penasaran terhadap Papua. Seperti apa bunyi genderang? Di mana Wamena? Bagaimana suasana hutan yang lebat itu? Kenapa genderang ini “dikembalikan” oleh orang Belanda ke Indonesia?
Cerita berlatar Indonesia Timur selalu menarik bagi saya, terlebih karena saat usia 20-an, saya tinggal di NTT selama beberapa tahun, dan di Papua Barat beberapa bulan. Di masa-masa itulah saya mulai mempertanyakan definisi “kesejahteraan” dan “kemajuan” versi orang-orang “modern.”
Indonesia Timur, bagi saya kala itu, adalah tempat yang penuh kekurangan dan kelebihan seperti tempat lainnya. Pengertian hidup yang terbelakang dan miskin yang sudah saya yakini dua dekade lebih mendadak goyah. Apa iya “miskin” berarti tidak punya uang dan akses terhadap fasilitas mewah, sementara kita bisa makan dari hasil bumi dan tangkapan laut, tanpa khawatir harus cari uang tiap hari? Apa iya “terbelakang” artinya tidak ada gedung tinggi dan orang-orang sibuk, sementara laut dan hutan menjadi halaman belakang yang… indah?
Buku ini hanya terdiri dari 75 halaman, cocok untuk teman duduk saya (dan mungkin kamu) yang sudah telanjur dewasa dan kurang lebih mulai mengerti (atau mulai mempelajari) hubungan Indonesia dengan Papua, dulu hingga kini. Saya menyarankan untuk membacanya pelan-pelan saja. Soalnya, ceritanya seru. Rasanya gatal deh, mau bikin semacam fanfiction-nya. Saya jadi tertarik membaca karya Djokolelono lainnya.

Chairumi Tyas Satiti, lahir di Magelang, menyukai buku dan berlama-lama di perpustakaan, juga gemar menulis dan mencatat—istilah kerennya: journaling. Koleksi bukunya lebih banyak dari koleksi bajunya. Sambil bekerja jarak jauh dari apartemen kecilnya, ia membuat benda berguna dari apa yang dipunya, contohnya tempat pena dari gelas plastik kopi kekinian. Ia tidak suka kopi dan durian, tetapi bisa menunjukkan di mana tempat ngopi dan makan durian terenak di Magelang. Cita-citanya saat ini adalah kembali berkebun bersama anak dan suaminya. Jika melihatnya di jalan, kamu bisa memanggilnya Chaty atau Tyas atau Keti.